
Dari SMAN 39 Cijantung Jakarta Timur, aku melesat ke Cikini Jakart Pusat. Tujuan? Taman Ismail Marzuki. Karena terlampau lama di SMAN 39, dan baru sore hari bisa meluncur, mau tak mau bersinggungan dengan jam pulang kantor.
Apa boleh buat, sampai TIM acara diskusi novel Lanang karya kawanku, Yonathan Rahardjo si dokter hewan itu, telah lagi usai. “Ke PDS saja. Kita di sana.” ucap Sihar di telpon. Gantinya, aku merapat ke Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin. Ada diskusi rutin ‘meja kerja budaya’ bersama Remy Sylado.
Sampai PDS, ternyata bahkan acara diskusi rutin itu pun baru saja usai. Jadinya dua-duanya tak kuikuti.
Akhirnya bersapa-sapa saja, berkangen-kangen, duduk berbicang-bincang tentang apa saja dengan Sihar Ramses Simatupang, Badri, Donny Anggoro, Martin Aleida, Hamsad Rangkuti, Remy Sylado, dan siapa lagi ya… kok lupa.
“Pulang kapan, Daniel?” tanya Martin Aleida.
“Belum tau, Bang Martin. Belum kutentukan.”
“Besok ada peluncuran buku Puthut EA. Oya, hari minggu diundang ke rumah Oey Hay Djoen. Yah, acara 7 harinya mungkin.”
Oey Hay Djoen, fungsionaris Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) dan anggota Dewan Konstituante (DPR-GR) mewakili PKI (Partai Komunis Indonesia) memang baru saja meninggal dunia pada 18 Mei lalu di usia 79 tahun.
Tak banyak yang dapat kuceritakan tentang Oey Hay Djoen kecuali membaca tentang dirinya dari berbagai referensi. Selain hanya beberapa kali bertemu, secara individu memang tak begitu kenal.
Tapi ada satu kenangan dengan Oey Hay Djoen ketika bertemu di acara 100 hari almarhum Pramoedya Ananta Toer di rumah Utan Kayu. Saat itu usai pengajian dan santap malam, Oei Hay Djoen pamit pulang. Diikuti dengan istri dan Mbak Dolorosa Sinaga.
“Mas Daniel, Om Hay Djoen mau pulang,” ujar Mbak Astuti Ananta Toer ketika melihatku sedang ngobrol dengan Yudhistira Ananta Toer di teras rumah.
“Om, ini Daniel,” tukas Mbak Astuti pada Oei Hay Djoen memperkenalkanku.
Oei Hay Djoen pun mengulurkan tangan menyambut tanganku. “Oh, kamu Daniel Mahendra?”
Aku kaget. “Ya…” jawabku cepat.
“Kamu dari Bandung kan?”
“Iya …”
“Ya-ya, saya tau kamu.”
Saat itu aku hanya bengong.
Kembali ke ruangan di PDS.
“Kemana kita?” tanya Sihar.
“Bersekutu lagi?” timpal Badri.
“Entahlah. Aku lapar.” jawabku. “Tapi sebentar, dengar-dengar bulan Juli nanti ada acara seru ya, Bang Martin?” tanyaku pada Martin Aleida sembari melirik Badri.
Yang ditanya tersenyum dengan mata mengerling menggoda, “Ya, ada yang mau naik ranjang!”
Perempuan bernama Yuni yang tadi sempat dikenalkan padaku hanya mesam-mesem. Rupanya Badri memang hendak melangsungkan pernikahan pada 12 Juli 2008 nanti bersama Yuni.
“Mestinya jangan Juli. Juni saja. Kalian berdua kan lahir di bulan Juni. Sayang banget momennya kalau dijatuhkan di bulan Juli.” ucapku memprotes.
“Aku sholat dulu…” ujar Badri ngeloyor pergi tak mau membahas.
“Hah?!! Sebentar! Sebentar! Mau ngapain?! Sholat?! Badri sholat?! Badri sekarang sholat?!! Wow!!!” tanyaku terbelalak. Kawan-kawan lain hanya ngakak.
“Wow!! Wow!! Wow!! Hebat juga kamu, Yun, bisa membuat Badri sholat!” sambungku masih juga terbelalak ngakak.
“Orang di rumah Mas Badri juga pada heran Mas, waktu siang-siang Mas Badri tiba-tiba ngambil wudhu.”
“Hahaha!!” aku tambah ngakak.
“Tapi semua sholat dia baca keras-keras. Nggak Dzuhur, nggak Ashar.”
Aku tambah terpingkal-pingkal. “Nggak pa-pa… Nggak pa-pa… Ini progress ini! Dahsyat ini! Ibunya aja sampai setengah hidup nyuruh dia sholat.”
Akhirnya sebagai penutup bincang-bincang PDS, bincang-bincang dilanjutkan di meja nasi goreng di TIM.
“Mau nonton teater nggak?” ajak Badri.
“Aku pulang ke Bandung kayaknya.”
“Lho, kok? Nggak nginap?”
“Kau kan mesti mengantar Yuni…”
“Lho, kita menganut persamaan gender kok,” timpal Yuni tersenyum, “Bisa pulang sendiri-sendiri.”
“Halah. Itu hanya ramai di meja diskusi. Pada alam nyata, tetap saja minta Mas Badri mengantarmu pulang kan…”
“Hehehe! Iya sih.” ucap Yuni nyengir.
Aku memutuskan pulang. Aku hendak menikmati malam ini seorang diri. Di langit bulan bundar tampak benderang. Berarti ada teman perjalanan, pikirku sembari menatap langit.
“Aku pergi!” ujarku mengendong ransel.
Tiba-tiba terdengar lagu Haruskah Pergi ciptaan Iwan Fals dan Indra Lesmana:
Sering aku merasa
Tak mengerti dengan apa yang ada
Melihat dari kegelapan
Mencoba mengurai makna
Begitu banyak yang terjadi
Begitu banyak yang tak kupahami
Orang saling membenci
Membunuh dan melukai
Perang masih terjadi
Bencana bertubi tubi
Kerinduan tercampak
Kesepian merajai
Aku ingin pergi
Meninggalkan ini semua
Menemani senja
Yang sedang berduka
Aku harus pergi
Meninggalkan semua ini
Menemui kamu
Yang mengajak bercinta
Air mata nyaris jatuh
Di pelataran rumah yang teduh
Ayat-MU terkapar
Di lemari lemari berdebu
Ada apa gerangan
Mengapa mesti tergesa gesa
Tak bisakah tenang
Menikmati bulan penuh dan bintang
Lalu mengarungi waktu
Dengan lapar yang menyakitkan
Menyikapi semua
Dengan kesabaran
Aku ingin pergi
Meninggalkan ini semua
Menemani senja
Yang sedang berduka
Aku harus pergi
Meninggalkan semua ini
Menemui kamu
Yang mengajak bercinta
Jakarta, 23 Mei 2008, 21.30 wib.

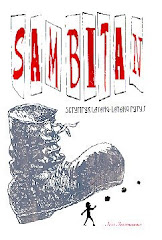



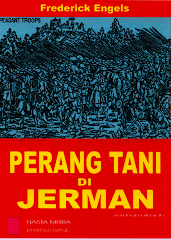


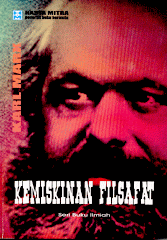


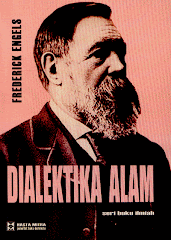
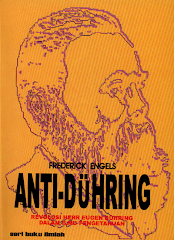
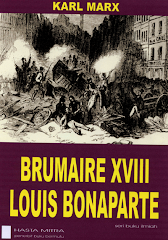

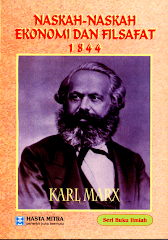
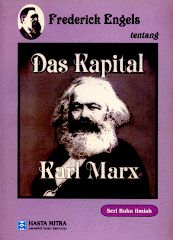
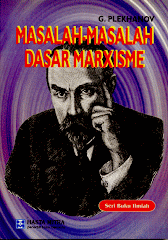
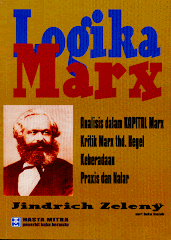
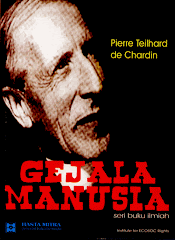


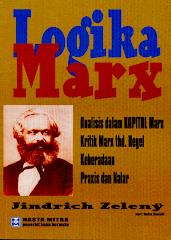

Tidak ada komentar:
Posting Komentar